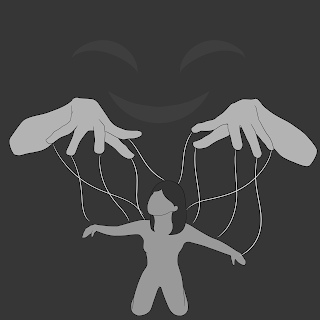.png) |
| Sumber: Beryl Bernay/Getty Images |
Oleh: Noki Dwi Nugroho
Pendahuluan
Tahun awal berdirinya suatu bangsa tak jarang terjadi gonjang-ganjing, seperti perebutan kekuasaan yang seringkali terdapat campur tangan pihak asing di dalamnya. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mengalami hal serupa ketika Republik genap berusia 20 tahun. Peristiwa yang diyakini sebagai perebutan kekuasaan antara militer dan kelompok komunis yang dikenal sebagai peristiwa G30S/Gestok/Gestapu ini meninggalkan tinta darah dalam catatan Indonesia. Tak ada yang menyangka bahwa peristiwa yang memakan korban 6 perwira tinggi dan 1 perwira muda ini berbuntut pada penangkapan juga pengasingan orang yang tertuduh sebagai komunis, pembubaran partai komunis, bahkan genosida politik.
Gerakan 30 September bukan hanya tentang pembantaian 7 perwira militer AD saja. Lebih dari itu, terjadi pula perebutan kekuasaan antara PKI dan kelompok kontra-PKI, yaitu partai oposisi, mahasiswa, dan angkatan darat. Konflik yang terjadi antara kedua kekuatan ini terlihat pada Pemilu 1955 dan masa demokrasi terpimpin. Pada masa itu, PKI sebagai partai posisi empat pemenang Pemilu 1955 dianggap terlalu dekat dengan Sukarno yang pada saat itu pula hubungan Indonesia dengan blok komunis sangat mesra. Hal inilah yang membuat kelompok anti-komunis sangat mendukung pembubaran Partai Komunis Indonesia dari bumi Nusantara.
Kondisi Republik saat itu menjadi sangat kacau pasca meletusnya peristiwa Gerakan 30 September. aksi demonstrasi besar-besaran, pembunuhan para terduga PKI, dan kerusuhan lain membuat kondisi Republik makin kacau. Kondisi seperti ini menjadi sangat rawan akan terjadinya perebutan kekuasaan, terlebih kepercayaan rakyat terhadap Presiden Sukarno menurun selepas peristiwa berdarah tersebut. Melihat keadaan politik Republik yang sedang kacau ini kemudian “dimanfaatkan” oleh Soeharto yang saat itu berpangkat Letnan Jenderal untuk tampil di hadapan rakyat Indonesia seakan dia lah pahlawan yang akan menstabilkan kondisi Republik. Berbekal surat perintah yang ditandatangani langsung oleh Presiden Sukarno, Soeharto melakukan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu untuk mengembalikan kestabilan negara, walaupun tindakan tersebut dianggap melewati batas dan menimbulkan kontroversi. Lantas bagaimana Soeharto bisa mendapatkan surat perintah tersebut? Bagaimana bisa surat perintah ini menimbulkan banyak sekali kontroversi? Dan apa saja dampak dari surat perintah yang digunakan Soeharto untuk menjaga kestabilan negara?
Mengenai Supersemar dan Kelahirannya
Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) atau SP 11 Maret adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno pada 11 Maret 1966. Surat ini berisi pemberian kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang “dianggap perlu” guna mengembalikan kestabilan negara pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Tak hanya itu, surat ini juga berisi perintah untuk mengamankan jalannya pemerintahan dan pengamanan keselamatan Presiden Sukarno beserta ajaran juga wibawanya. Kenyataannya, Soeharto hanya menjalankan apa yang menurut ia perlu guna menstabilkan kondisi Republik tanpa persetujuan dari Presiden Sukarno. Proses keberadaan Surat Perintah Sebelas Maret ini tidak bisa dikatakan hanya terjadi pada hari itu saja, sebelumnya sudah ada upaya untuk membujuk Presiden Sukarno agar memberikan kewenangan pada Soeharto melalui berbagai cara.
Asisten VII Menpangad (Menteri Panglima Angkatan Darat), Alamsjah Ratu Perwiranegara memberi usul pada Soeharto untuk mencoba membujuk Presiden Sukarno melalui 2 pebisnis yang sangat dekat dengan Presiden Sukarno, hal ini bertujuan untuk meminta Presiden Sukarno agar membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan memberi kewenangan pada Soeharto. Usul itu disetujui Soeharto dan pada 9 Maret 1966 dua pebisnis tersebut, yaitu Hasjim Ning dan Dasaad diutus untuk menemui Presiden Sukarno di Istana Bogor. Namun, “misi” 2 pebisnis ini gagal setelah mendapat amarah dari proklamator RI tersebut, bahkan beredar kabar yang mengatakan bahwa Hasjim Ning mendapatkan respon lemparan asbak dari Bung Besar akibat hal itu.
Setelah kegagalan upaya untuk membujuk Presiden melalui pendekatan orang yang dekat dengannya gagal, Soeharto mencoba lagi dengan melakukan pendekatan yang seakan mengancam Presiden dengan mengutus 3 perwira tinggi AD, yaitu Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amir Machmud, dan Mayjen Basuki Rachmat pada 11 Maret 1966. Di hari yang sama terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan kelompok militer “liar” (diduga pasukan pimpinan Mayjen Kemal Idris) yang menolak pembentukan Kabinet Dwikora II Yang Disempurnakan karena dianggap melibatkan orang-orang yang terlibat pada peristiwa G30S. Melihat kondisi sekitar Istana yang tidak kondusif, Presiden Sukarno meninggalkan Jakarta dan menuju Istana Bogor dengan menggunakan helikopter. Siang harinya, 3 perwira tinggi yang diutus Soeharto datang menemui Presiden untuk mengupayakan pemberian kewenangan kepada Soeharto. Singkatnya, ketiga perwira utusan Soeharto ini berhasil mendapatkan surat perintah yang telah ditandatangani oleh Presiden Sukarno dan menyerahkannya kepada Soeharto yang pada itu sedang sakit.
(Mis)Interpretasi Soeharto Terhadap Supersemar
Operasi gerak cepat dilakukan Soeharto setelah menerima surat perintah bertanda tangan Presiden yang sebelumnya telah diantar pada malam hari oleh tiga jenderal. Dengan berbekal SP, Soeharto melakukan tindakan pertamanya yang lain dan tidak bukan adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormas-ormasnya. Di malam yang sama, Soeharto bersama perwira tinggi AD mendiskusikan mekanisme pembubaran PKI. Setelah diskusi malam yang cukup panjang, pada pagi hari di 12 Maret 1966, melalui Radio Republik Indonesia (RRI) memberitakan perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormas-ormasnya. Hal ini sontak membuat AD, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan kelompok anti-PKI lain bersorak gembira. Setelah itu, para kelompok anti-PKI menggelar aksi besar-besaran setelah kemenangannya atas PKI. Kolonel Sarwo Edhie, komandan Resimen Pasukan Komando Pasukan Angkatan Darat (RPKAD) saat itu juga turut ambil bagian pada pawai dengan melakukan konvoi keliling kota Jakarta yang bertujuan untuk unjuk kekuatan. Merespon tindakan ini, Sukarno sangat marah melihat SP 11 Maret digunakan Soeharto untuk melakukan tindakan yang dilakukan tanpa persetujuannya.
Tindakan kedua yang dilakukan Soeharto dalam menginterpretasikan SP 11 Maret adalah menandatangani surat tertanggal 18 Maret 1966 yang berisi perintah penangkapan 15 menteri Soekarno kabinet Dwikora II Yang Disempurnakan yang dianggap pro kepada PKI. Beberapa nama menteri yang diringkus oleh Soeharto diantaranya:
1.Soebandrio (Wakil Perdana Menteri, merangkap Menlu)
2.Chaerul Saleh (Ketua MPRS, merangkap Wakil Perdana Menteri III)
3.Surachman (Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Desa)
4.Setiadji Reksoprodjo (Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan)
5. Oei Tjoe Tat (Menteri Negara Diperbantukan Kepada Presidium)
6.Jusuf Muda Dalam (Menteri Urusan Bank Sentral, merangkap Gubernur Bank Indonesia
7.Achmadi Hadisoemarto (Menteri Penerangan)
8.Mochammad Achadi (Menteri Transmigrasi dan Koperasi)
9.Soemardjo (Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan)
10.Armunanto (Menteri Pertambangan)
11.Soetomo Martopradoto (Menteri Perburuhan)
12.Astrawinata (Menteri Kehakiman)
13.Junius Kurami Tumakaka (Menteri Sekretaris Jenderal Front Nasional)
14.Mayjen. Dr. Soemarno Sosroatmodjo (Menteri Dalam Negeri, merangkap Gubernur DKI Jakarta)
15.Letkol. Imam Syafei (Menteri Urusan Pengamanan)
Militer loyalis Sukarno pun ikut mendapatkan perlakuan buruk dari Soeharto karena dianggap menjadi penghambat bagi Soeharto dalam mencapai kekuasaannya. Atas dalih G30S, para loyalis Sukarno mendapatkan tindakan buruk seperti diturunkan dari jabatannya, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Ibrahim Adjie misalnya, Ia adalah seorang loyalis Sukarno yang juga saat itu menjabat sebagai panglima Kodam III/Siliwangi, Ia diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Mayjen Hartono Rekso Dharsono. Kemudian, komandan Korps Komando (KKO) Angkatan Laut (sekarang korps marinir), Letjen Hartono juga harus didepak dari jabatannya dan dijadikan sebagai duta besar Indonesia untuk Korea Utara pada awal kepemimpinan Soeharto. Sejarah mengenal sosok Hartono atas keberpihakannya kepada Sukarno, Ia dengan lantang berkata “Putih kata Bung Karno, putih kata KKO. Hitam kata Bung karno, hitam kata KKO”. Di sisi lain, Hartono juga dikenal atas kontroversi kematiannya, versi resmi dari pemerintah menyebut alasan kematian dari Hartono adalah bunuh diri. Namun, banyak orang terdekatnya menganggap kematiannya akibat dari upaya Orde Baru dalam memberangus para loyalis Sukarno.
Kembali ditekankan bahwa Supersemar adalah surat perintah yang ditujukkan juga untuk melakukan pengamanan keselamatan Presiden Sukarno beserta ajaran juga wibawanya. Namun, perintah ini “gagal” dijalankan oleh Soeharto karena ia hanya mengambil tindakan yang dirasa perlu tanpa persetujuan Presiden Sukarno, yang akhirnya membuat Presiden kecewa.
Dikutip dari Historia.id, M. Jusuf merespon hal ini dengan mengatakan bahwa “kemenangan perjuangan ini sudah mencapai tiga perempat jalan, yaitu pelarangan Partai PKI, perombakan kabinet, dan menteri pro-komunis yang sudah disingkirkan. Namun, yang menjadi ketakutan bagi kelompok Soeharto ialah jika suatu saat Bung Karno mencabut Supersemar”. Dalam mengatasi ketakutannya, Soeharto dengan liciknya menetapkan Supersemar menjadi TAP MPRS pada sidang tahun 1966 yang dituangkan pada Tap No. IX/MPRS/1966. Dengan menetapkan Supersemar menjadi TAP MPRS ini membuat Presiden Sukarno tidak bisa mencabut Supersemar dari Soeharto.
Kontroversi Supersemar
Berbagai kontroversi menyelimuti Supersemar sepanjang pelaksanaannya, misinterpretasi Soeharto dalam menjalankan Supersemar dan akal-akalan penetapan Supersemar menjadi TAP MPRS adalah sebagian kecil dari kontroversi Supersemar.
Berakhirnya era kepemimpinan rezim militeristik yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun membawa dampak besar bagi keterbukaan sejarah masa lalu. Soekardjo Wilardjito misalnya mengaku pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta bahwa Ia adalah mantan prajurit pengawal Presiden Soekarno yang saat itu menjadi saksi atas peristiwa penandatanganan Supersemar yang ditandatangani Presiden Sukarno. Pada pengakuannya, ia bersaksi bahwa salah satu perwira tinggi AD yang terlibat pada peristiwa penandatanganan Supersemar, Maraden Panggabean menodongkan pistol FN 46 yang berada pada kondisi terkokang kepada Presiden Sukarno. Setelah pengakuannya yang menggemparkan ini, beberapa tokoh turut membantah hal ini. M. Panggabean membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak hadir pada peristiwa tersebut. M. Jusuf pada saat itu juga turut membantah pengakuan Soekardjo, dia menyebut bahwa ini semua omong kosong. Buntut dari pengakuannya, Soekardjo harus berurusan dengan hukum, ia didakwa atas pemberitaan berita bohong.
Hal kedua yang membuat kontroversi adalah respon Presiden Soekarno terhadap tindakan yang dilakukan Soeharto atas Supersemar yang sudah ia berikan. Pada pidato berjudul Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah) yang dibacakan pada 17 Agustus 1966, Presiden menyebut dengan lantang bahwa Supersemar bukanlah transfer of sovereignty dan bukan pula transfer of authority. Selanjutnya Presiden menekankan kembali bahwa pada awalnya dan memang seharusnya SP 11 Maret menjalankan perintah untuk pengamanan keselamatan, wibawa, juga ajaran presiden dan perintah untuk mengamankan jalannya pemerintahan. Jelas pada saat itu keberadaan Presiden tidaklah berada pada posisi yang menguntungkan, setelah Supersemar dijadikan TAP MPRS, Presiden tidak dapat mencabut Supersemar.
Kontroversi Supersemar selanjutnya adalah mengenai tiga versi Supersemar yang saat ini tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Mengutip dari Historia.id, ketiga versi Supersemar ini tidak bisa dikatakan otentik, hal ini dibuktikan setelah mengalami uji forensik. Ketiganya juga dapat dikatakan unik karena memiliki versinya masing-masing. Versi pertama didapatkan dari Pusat Penerangan TNI AD (Puspen TNI AD), Supersemar versi ini dicirikan dengan hanya terdapat satu lembar, bertanda tangan Sukarno (Huruf “u” pada nama Sukarno ditulis dengan “oe”), diketik rapi justify. Versi kedua dari Supersemar diperoleh dari Sekretariat Negara, versi ini memiliki dua lembar dan tanpa tanda tangan Sukarno, hanya tertanda nama Sukarno saja (Penulisan nama Sukarno ditulis dengan huruf “u”). Dan versi ketiga diperoleh dari Yayasan Akademi Kebangsaan pada tahun 2012. Pada versi ini hanya terdapat satu lembar dengan kondisi sobekan pada sisi kanan dari surat dan bertanda tangan Sukarno (Nama Sukarno ditulis dengan huruf “u” sama seperti pada versi Sekretariat Negara).
Akhir Supersemar yang Mengakhiri Sukarno
Pergolakan yang terjadi pada akhir September 1965 telah membuat pengaruh kekuasaan Presiden Sukarno menurun, yang diperparah setelah dijalankannya Supersemar yang menimbulkan banyak kontroversi.
Sidang Umum IV MPRS pada Juni 1966 menandakan awal dari kemenangan Soeharto atas Sukarno. Pada sidang ini Sukarno membacakan sebuah pidato pertanggungjawaban yang berjudul Nawaksara, pidato pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Indonesia setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September. Sidang ini menetapkan Supersemar menjadi TAP MPRS No. IX dan pada sidang ini pula MPRS mencabut ketetapan MPR mengenai jabatan presiden seumur hidup Presiden Sukarno, hal ini membuat MPRS menetapkan Soeharto menjadi pejabat presiden hingga dilantiknya Soeharto menjadi Presiden pada 26 Maret 1968.
Penutup
Supersemar telah berusia lebih dari setengah abad, begitu pula kontroversinya. Penelusuran jawaban terkait pertanyaan atas kebingungan sejarah perlu kita cari. Dampak dari Supersemar bukan hanya tentang hilangnya kekuasaan Sang Proklamator. Lebih dari itu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang menjadi korban atas tuduhan sebagai kelompok komunis. Bukan hanya itu saja, dampak dari Supersemar ialah membuat Indonesia dipimpin oleh rezim militeristik yang membungkam pandangan kritis rakyat selama 32 tahun lamanya yang bahkan warisan buruknya masih berbekas dan bisa kita rasakan hingga saat ini.
Daftar Pustaka
Danang, M. (2021, Maret 11). Supersemar, Transisi Kekuasaan Soekarno kepada Soeharto. Retrieved from Kompaspedia: https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/supersemar-transisi-kekuasaan-soekarno-kepada-soeharto?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/supersemar-transisi-kekuasaa
detikNews. (2013, Maret 6). Soekardjo Wilardjito, Saksi Supersemar Meninggal Dunia. Retrieved from detikNews: https://news.detik.com/berita/d-2186816/soekardjo-wilardjito-saksi-supersemar-meninggal-dunia#:~:text=Yogyakarta%20%2D%20Soekardjo%20Wilardjito%20(86),Desa%20Sidomulyo%2C%20Kecamatan%20Godean%20Sleman.
Isnaeni, H. F. (2015, Maret 12). Supersemar dan Tafsir Soeharto. Retrieved from Historia.id: https://historia.id/politik/articles/supersemar-dan-tafsir-soeharto-DwRgA/page/2
Sitompul, M. (2018, Maret 11). Memburu Surat Sakti. Retrieved from Historia.id: https://historia.id/politik/articles/memburu-surat-sakti-DbeW2/page/2
Sitompul, M. (2018, Maret 15). Meringkus Loyalis Sukarno. Retrieved from Historia.id: https://historia.id/politik/articles/meringkus-loyalis-sukarno-6aql7/page/1
Tim Majalah Historia. (2019). Supersemar: Cara Soeharto Mendapatkan Kekuasaan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Wanhar, W. (2015, Maret 10). Misi Pengusaha Sebelum Supersemar. Retrieved from Historia.id: https://historia.id/politik/articles/misi-pengusaha-sebelum-supersemar-vqBBP/page/1