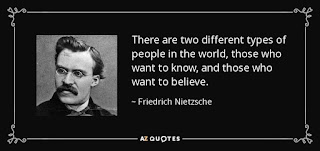Senin, 4 April 2016
yang lalu LPPMD Unpad melaksanakan kegiatan diskusi buku “Melawan Liberalisme
Pendidikan”. Dalam diskusi buku karangan Darmaningtyas, Fahmi Panimbang, dan
Edi Subkhan tersebut, hadir sejumlah mahasiswa dari kader LPPMD maupun
non-LPPMD. Adapun materi yang dibahas dalam diskusi tersebut tentu saja perihal
pendidikan tinggi yang pada era dewasa ini cenderung digunakan atau dijadikan
oleh sebagian pihak sebagai ladang bisnis, seperti yang dinyatakan oleh Putri—salah
satu peserta diskusi—yang mengatakan bahwa pendidikan kali ini selalu
menekankan pada aspek investasi dan memperoleh keuntungan dari sesuatu yang
diinvestasikan.
Pendidikan
Tinggi di Indonesia sendiri sebetulnya
telah mengalami liberalisasi sejak dimulainya reformasi sesuai dengan PP No. 61
Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, yang
kemudian diperkokoh dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 53 yang mengatur soal
pembentukan badan hukum pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Hal ini jualah yang kemudian menginisiasi UU No. 9 tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan (BHP). UU tentang BHP sendiri sudah dibatalkan Mahkamah
Konstitusi pada 31 Maret 2010. Menurut aspek hukum, UU BHP jelas
inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab
menyelengggarakan dan membiayai pendidikan anak bangsa, namun kemudian malah
membebankan wewenang kepada institusi pendidikan (Febriantanto, 2010). Singkatnya,
semua peraturan-peraturan tersebut dianggap sebagai segenap usaha dalam
meliberalisasi pendidikan dengan dalih otonomi kampus, dan lain-lain.
Pada
dasarnya, liberalisme pendidikan tinggi mempunyai dampak negatif berupa
hilangnya ‘roh’ dari pendidikan itu akibat terjadinya pergeseran orientasi yang
mana hal ini disebabkan oleh suatu usaha untuk menjadikan institusi pendidikan
sebagai sarana bisnis. Di sisi lain, menurut salah satu peserta diskusi, pendidikan
dewasa ini dirasa lebih mengutamakan daya saing ketimbang daya guna. Sehingga,
tidak heran jika banyak pelajar atau mahasiswa menjadi stress karena harus selalu mampu memenuhi tuntutan-tuntutan dalam
persaingan.
Oleh
karena itu, perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak terkait dengan jalannya
proses pendidikan di tanah air terutama pengawasan oleh kalangan mahasiswa itu
sendiri agar kritis dan berani bersuara terhadap kebijakan-kebijakan yang akan
dilaksanakan. Hal ini tentu saja bertujuan agar kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan dapat menguntungkan semua pihak. Mari lawan liberalisasi pendidikan (tinggi)!
(Annadi M.A dan Aldo F.N.)