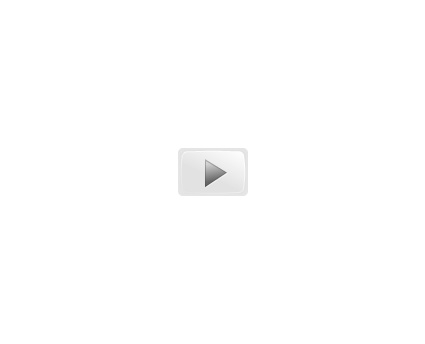Oleh: Alfathri Adlin, editor Pustaka Matahari, mahasiswa S-2 jurusan filsafat di STF Driyarkara
Suatu ketika, ada seorang lelaki
yang menyampaikan keluhannya kepada Ibn ‘Arabi ihwal kondisi zaman yang
dipandangnya semakin dekaden. Menurutnya, betapa sulit mencari orang beriman di
masa itu, betapa orang-orang lebih menyukai kehidupan dunia. Ibn ‘Arabi
bertanya, sudah berapa banyak negeri yang didatangi lelaki tersebut, sudah
berapa banyak orang yang dia jumpai di berbagai negeri. Ternyata, berbeda
dengan Ibn ‘Arabi, lelaki tersebut bisa dikatakan jarang melakukan perjalanan
ke berbagai negeri. Mengetahui hal tersebut, Ibn ‘Arabi kembali bertanya,
bagaimana lelaki tersebut bisa mengeluhkan tentang dekadensi zaman, sementara
negeri dan orang yang pernah dijumpainya hanya sedikit.
Bagaimanapun, keluhan lelaki tersebut setidaknya memperlihatkan
kecenderungan yang senantiasa berulang di setiap masa, yaitu pandangan tipikal
dari orang-orang yang punya perhatian lebih mendalam terhadap ajaran-ajaran
agamanya dengan memandang bahwa mereka tengah hidup di zaman yang dekaden. Di
Tanah Jawa, misalnya, kita juga mengenal istilah Zaman Edan yang dilontarkan
oleh pujangga sufi bernama Ronggowarsito. Bukan tidak mungkin bahwa di setiap
dekade selalu saja ada yang menafsirkan bahwa ramalan Ronggowarsito tersebut
tengah berlangsung. Begitu pula di kalangan umat Islam secara luas, berbagai
hadis tentang tanda-tanda datangnya kiamat, pada setiap masa dapat ditafsirkan
juga tengah berlangsung. Dalam novel The
Name of the Rose karya Umberto Eco yang berlatar Abad Pertengahan,
diceritakan bagaimana serangkaian pembunuhan yang terjadi ditafsirkan memiliki
pola yang sesuai dengan nubuwah Kitab Wahyu tentang kiamat. Tentu saja hal
tersebut membuat para biarawan penghuni biara menjadi panik dan histeris.
Karena itu, di masa kapan pun, tampaknya orang-orang yang memiliki perhatian
lebih terhadap agama senantiasa merasa tengah berada di masa terburuk dari
seluruh masa.
Kecenderungan seperti itu pulalah yang seringkali memicu romantisme di
kalangan agama, yaitu, kecenderungan untuk melihat bahwa masa lalu lebih baik
daripada masa sekarang, dan yang harus diupayakan adalah mengembalikan keadaan
masa sekarang menjadi seperti masa lalu. Pemicu umum dari kecenderungan
romantisme ini biasanya ditumbuhkan oleh kebiasaan untuk bercermin dan
mengambil pembelajaran dari figur terpilih serta peristiwa di masa lalu. Dapat
dikatakan bahwa hampir semua sendi hukum yang menyangga agama-agama besar saat
ini adalah sesuatu yang dirumuskan dan dicontohkan oleh figur terpilih dan
peristiwa di masa lalu, karena diyakini bahwa sendi hukum tersebut memiliki
sifat-sifat perenial dalam dirinya, sehingga dapat berlaku di setiap masa. Namun,
ada konsekuensi lazim dari pandangan romantisme ini—apabila terlalu berlebihan—yaitu,
mengalihkan orang dari realitas yang melingkupinya; realitas bahwa dia hidup di
hari dan detik ini.
Namun, di sisi
lain muncul juga kesadaran akan perubahan realitas, budaya dan masa yang
mendorong adanya upaya rekontekstualisasi dan reinterpretasi ajaran agama.
Namun, bentuk-bentuk manifestasi rekontekstualisasi dan reinterpretasi tersebut
sangat beragam, bergantung kepada model pembacaan yang dipengaruhi oleh
kondisi sosial dan budaya, lingkungan, tingkat pemahaman, tingkat literasi,
intelektualitas, nilai dan ideologi. Singkatnya, segala hal yang emlingkupi
manusia yang mempengaruhi cara pembacaannya terhadap agama. Yasraf Amir Piliang
pernah menguraikan lima jenis pembacaan atas kitab suci, yaitu:
1. Pembacaan
denotatif: membaca teks Kitab Suci melalui pembacaan lateral sehingga
menghasilkan makna-makna yang langsung atau eksplisit.
2. Pembacaan
konotatif: pembacaan teks Kitab Suci secara kontekstual, dengan mengkaitkan
yang tersurat secara lateral dengan berbagai bentuk emosi, perasaan, sentimen, perhatian,
kepentingan, hasrat dan kepercayaan di tingkat individu maupun sosial, untuk
menemukan makna implisit.
3. Pembacaan
dekontekstual: pembacaan konotatif yang tidak konstekstual dengan mengkaitkan
teks kepada makna-makna implisit di luar konteks awal teks.
4. Pembacaan
fetisistik: pembacaan mistifikasi yang melepaskan teks dari konteks
komunikatifnya, menetralkannya dan mengisinya dengan kekuatan mistik tertentu.
5. Pembacaan
dekonstruktif: pembacaan yang
melepaskan teks dari konteks komunikatifnya dengan menjadikannya sebagai
penanda baru tanpa henti untuk menghasilkan perbedaan dan permainan kultural
semata[1]
Kelima bentuk pembacaan tersebut merupakan landasan
dari berbagai bentuk manifestasi resistensi dan gaya hidup beragama. Namun,
benarkah semua ungkapan keberagamaan yang termanifestasikan dalam kehidupan
sehari-hari selalu bermuatan resistensi?
Agama sebagai Resistensi
Dikatakan bahwasanya budaya dan
gaya hidup merupakan sebentuk resistensi terhadap yang natural. Demikian pula
hanya dengan agama, dalam dirinya terdapat potensi resistensi, bukan pada yang
natural, tapi justru lebih sering tertuju kepada budaya atau gaya hidup itu
sendiri. Umumnya, agama-agama besar mengajarkan kepada para penganutnya agar
resis terhadap kehidupan dunia. Bahwa banyak dosa menodai jiwa manusia
diakibatkan oleh persentuhan atau hanyut dalam kehidupan duniawi. Dalam hal
ini, agama banyak memberikan panduan—mulai dari yang abstrak-konseptual hingga
yang konkrit-praktis—tentang bagaimana sebaiknya menjalani hidup di dunia. Umumnya,
manusia ideal dalam pandangan agama adalah manusia yang hidup seperti ikan
laut, yaitu, hidup dan berenang di laut yang asin namun tidak menjadikan
tubuhnya seasin air laut. Dalam hal ini, agama merupakan suatu keadaan atau state yang tetap terjaga (conserve) dalam perjalanan waktu. Kepenjagaan
diri ini biasanya diturunkan dari aspek-aspek hukum dan normatif agama yang dimanifestasikan
dalam kehidupan sehari-hari, serta penghayatannya. Namun, manifestasinya pun
sangat beragam karena, seperti diutarakan di atas, semua itu sangat bergantung
pada model-model pembacaan atas berbagai teks keagamaan.
Misalnya saja, terkait dengan penciptaan dan asal-usul
manusia, umumnya agama mempunyai jawaban final yang bersifat teleologis. Bahwa
manusia diciptakan dalam citra Tuhan dan menjadi wakilnya di muka bumi dengan
mengemban misi hidup khusus; bahwa manusia itu terusir dari surga dan turun ke
bumi dikarenakan manusia pertama—dalam tradisi Yudeo-Kristiani dan Islam adalah
Adam—telah melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi; bahwa manusia harus
bekerja keras di dunia ini agar bisa mendapatkan kehidupan yang menyenangkan di
akhirat nanti, dan berbagai jawaban telelologis lainnya. Namun, jawaban seperti
ini memang bersifat dogmatis dan menuntut kepercayaan penuh terlebih dahulu dari
para penganutnya, dan tak jarang terkesan melarang para penganutnya untuk
mempertanyakan lebih jauh hal tersebut. Misalnya, dulu ketika Zaman Kegelapan
di Eropa, Gereja pernah melarang orang untuk mempelajari pengetahuan, sebab
buah khuldi yang dimakan oleh Adam dan Hawa sehingga mereka berdua terusir dari
surga adalah buah pengetahuan. Karena itu, misalnya, ketika Coppernicus dan
Gallileo mengemukakan postulat bahwa matahari sebagai pusat peredaran planet, hal
itu berlawanan dengan keyakinan Gereja bahwa bumilah yang menjadi pusatnya,
maka Gereja pun berreaksi sangat keras terhadap postulat tersebut. Namun, setelah muncul Renaisans dan Gereja mulai
ditinggalkan karena sikap konservatifnya terhadap pengetahuan serta
doktrin-doktrin lamanya yang banyak terbukti bertentangan dengan perkembangan
pengetahuan, maka perlahan-lahan Gereja pun mulai mengubah sikapnya. Namun, di
abad dua puluh terjadi lagi sebuah peristiwa menarik yang menggambarkan
hubungan gereja dengan pengetahuan. Pernah diceritakan bahwa suatu ketika,
Vatikan mengadakan semacam pertemuan ilmiah dengan mengundang Stephen
Hawking sebagai salah satu pembicaranya. Pada saat itu, Paus Yohannes Paulus
berpidato bahwa Gereja tidak akan lagi menjatuhkan hukuman mati kepada para
ilmuwan seperti yang dilakukannya pada Zaman Kegelapan dulu. Namun, Sri Paus
menganjurkan agar para ilmuwan hanya mengutak-atik seputar permasalahan pasca penciptaan
alam semesta, dan tidak mencoba mengutak-atik permasalahan pra-penciptaan.
Mendengar hal tersebut, Stephen Hawking langsung berkemas untuk pulang, karena justru
makalah yang hendak dia sampaikan dalam pertemuan tersebut adalah rumusannya
tentang pra-penciptaan alam semesta, dan Hawking tidak mau menjadi Coppernicus
dan Gallileo berikutnya di abad dua puluh.[2]
Hal ini membuktikan bahwa hubungan agama dan pengetahuan (sekular) masih tidak
selalu serasi.
Memang, pada umumnya agama mengemukakan doktrin tentang hierarki alam dan
realitas, serta menyatakan bahwa manusia itu berasal dari alam dan realitas
yang lebih tinggi daripada alam dan realitas dunia ini. Dalam kehidupan di
dunia ini, manusia harus menyiapkan dirinya guna menghadapi kematian yang akan
memindahkannya ke alam dan realitas lain yang lebih tinggi. Agama juga
mengajarkan manusia untuk berbuat baik, karena segala perbuatan baik itulah
yang akan menjadi bekal di kehidupan berikutnya. Jawaban-jawaban eskatologis dari
agama tersebut seringkali mendapatkan tantangan dan sangkalan dari kalangan
ilmuwan maupun filsuf, terlebih pada awal masa Renaisans hampir semua ilmuwan
dan filsuf cenderung “ateis” karena terluka oleh sikap Gereja yang
anti-pengetahuan. Immanuel Kant bahkan menyatakan bahwa dengan Renaisans
manusia telah keluar dari era kekanak-kanakannya ke arah era kedewasaannya.
Selain itu, Kant pun berpandangan bahwa surga dan neraka itu dibutuhkan untuk
konvergensi moral, karena apabila tidak ada ide tentang surga dan neraka, maka
dimanakah orang-orang yang berdosa akan mendapatkan sangsinya? Selain itu, terlihat
juga bahwa sikap agnostik tersebut muncul dari Barat bersamaan dengan Renaisans.
Namun, sikap agnostik ini pun kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia dan
kini banyak diadopsi oleh orang-orang Timur. Bisa jadi, sikap agnostik dari
kalangan pemikir Barat mengalami pelunakan menjadi sikap skeptis di kalangan
pemikir Timur, namun umumnya tanpa trauma luka karena agama seperti yang
dialami para pemikir Barat. Ada satu uraian yang menarik dari Ernest Gellner
yang banyak meneliti dan menulis tentang masyarakat Muslim. Gellner
mengemukakan bahwa masyarakat Muslim itu ternyata sangat resis terhadap sekularisasi.[3] Dalam agama Islam sering mengemuka anjuran untuk
mengakhiratkan kehidupan dunia. Namun, dalam sejarah Islam juga bermunculan
para tokoh yang berpikiran skeptis terhadap ajaran-ajaran agama Islam, yang
menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara rasional. Akan tetapi, pemikiran dan
tafsiran mereka tidak bisa serta merta dikatakan sekular, kecuali mungkin oleh
golongan yang lebih puritan atau fundamentalis. Misalnya, Ibnu Sina
berpandangan bahwa pintu surga itu ada 8 sedang pintu neraka ada 7. Nah,
seorang mukmin yang baik itu memiliki 8 ciri, tapi apabila kurang satu saja
ciri tersebut—dan menjadi 7 ciri—maka itulah neraka.
Untuk zaman sekarang, filsafat dipandang lebih bisa mewadahi kecenderungan
manusia untuk berpikir bebas, untuk mengkritisi pandangan deterministik dari
agama ihwal manusia. Agama seringkali mengajarkan bahwa ada sebuah kebenaran
yang sifatnya abadi, murni dan tak terubah, sementara filsafat teramat sangat
meragukan klaim agama tersebut, karena menurut filsafat kebenaran itu adalah
konstruksi ideologis semata. Selain itu, filsafat Barat pun banyak melahirkan
pemikir-pemikir yang menyarankan keyakinan tentang kehendak bebas. Deleuze
& Guattari, misalnya, merupakan pemikir abad 20 yang paling lantang
menyuarakan ketidakpercayaannya tentang doktrin blue-print manusia, bahwa manusia memiliki cetakan primordial. Isu
budaya vs alam (nature vs culture) memang merupakan isu yang cukup
kental mewarnai filsafat abad 20. Selain itu, terkait dengan perubahan zaman,
ternyata secara fenomena, sains dan teknologi lebih bisa memberikan bukti
“kemajuan” secara kongkrit. Bahkan beberapa temuan sains dan teknologi malahan
seperti mematahkan argumen-argumen agama tentang kuasa Tuhan. Misalnya, ketika ditemukan
teknologi kloning, seakan itu menumbangkan “hak prerogatif” Tuhan untuk
mencipta makhluk. Ada cetusan yang cukup menarik dari Bambang Sugiharto, bahwa
seringkali Tuhan yang digambarkan para filsuf itu adalah Tuhan yang kaku,
dingin, pucat; Tuhan di atas kertas. Namun, pada kenyataannya, Tuhan yang
digeluti dalam kehidupan keseharian manusia tidaklah bermasalah. Baik-baik saja
malah.
Seperti telah dikemukakan sebelumnya, resistensi agama memang justru lebih
sering tertuju kepada yang budaya ketimbang yang alami. Terlebih setelah
Renaisans, secara fenomena umum, agama pun terlihat lebih sering distereotipkan
sebagai penyebab penolakan, konservatifisme, bahkan peperangan, dikarenakan
sikap reaktif, romantisme dan fundamentalisme dari sejumlah pengikutnya.
Walaupun demikian, sejumlah pengikut lainnya malah mencoba beradaptasi dan
melakukan rekontekstualisasi ajaran-ajaran agama. Di kalangan cendekiawan
muslim, misalnya, marak berbagai gerakan untuk melakukan islamisasi
pengetahuan. Umumnya mererka berkeyakinan bahwa ilmu itu bebas nilai, namun
faktor manusianyalah yang membuat ilmu itu bisa bertentangan dengan kehendak
Tuhan. Namun, apabila ditelusuri secara lebih mendalam, kebanyakan gerakan
islamisasi pengetahuan itu lebih banyak klaimnya ketimbang argumentasi
ilmiahnya.
Resistensi dan Gaya Hidup
Gaya visual seringkali
menyatu dengan gaya
hidup, karena dalam hidupnya manusia tidak bisa lepas dari bahasa visual dua maupun
tiga dimensi. Gaya merupakan suatu sistem bentuk dengan kualitas dan
ekspresi bermakna yang menampakkan kepribadian atau pandangan umum suatu
kelompok. Selain itu, gaya juga merupakan wahana ekspresi di masyarakat yang
mencampurkan nilai-nilai tertentu dari agama, sosial dan kehidupan moral
melalui bentuk-bentuk yang mencerminkan perasaan. Semua manusia adalah subjek
gaya sehingga kecenderungan suatu masyarakat dapat dianalisis melalui spektrum
gaya. Gaya biasanya menuntut bentuk yang konstan dari pemakainya, sehingga dari
hal itu orang bisa menilai tentang ciri-ciri suatu gaya hidup, bahkan gaya
peradaban. Namun, dalam perkembangan industri massa seperti saat ini, gaya
hidup dapat diidentifikasi melalui artefak atau objek desain yang dikenakan
oleh seseorang. Bahkan, gaya pun mempunyai susunan sintagmatiknya, sehingga
bisa dikatakan bahwa gaya hidup adalah mosaik artefak dan ide. Gaya itu dapat dipelajari karena bersifat artifisial dan
sadar diri, serta mengenal masa hidup (lahir, muda, dewasa, mati). Penggayaan (styling) merupakan ciri-ciri gaya yang
dengan sengaja dilebih-lebihkan, namun penggayaan yang ekstrim akan memunculkan
penolakan sebab masyarakat sangat rapuh terhadap perubahan gaya yang ekstrim.
Di kalangan masyarakat tradisional, segmentasi kelas
sosial terbagi sangat jelas, baik melalui gaya visualnya yang relatif tidak
banyak berubah. Peter York menyatakan bahwa dibandingkan dengan saat ini,
masyarakat tradisional hidup dalam penjara gaya. Sedang dalam masyarakat
modern, gaya memang berkembang pesat namun memperlihatkan ketiadaan acuan akan
nilai tertinggi (sekular). Dan dalam sistem globalisasi, batas-batas budaya
lokal, nasional maupun regional pun terkikis habis, sehingga arus gelombang
gaya hidup global dengan mudahnya berpindah-pindah tempat dengan perantara
media massa. Gaya hidup yang berkembang saat ini lebih beragam, mengambang dan
tidak hanya dimiliki oleh satu masyarakat khusus, bahkan para konsumer pun
dapat memilih dan membeli gaya hidupnya sendiri, karena suatu gaya hidup
menawarkan identitas.
Singkatnya, gaya hidup yang berkembang dalam masyarakat
yang hidup dalam zaman industri massa seperti saat ini adalah gaya hidup dan budaya
pop. Sering dikatakan bahwa budaya pop itu identik dengan budaya massa, karena
terlahir dari penggunaan berbagai kombinasi produk industri massa. Seperti
dikemukakan oleh Heidegger, manusia itu adalah makhluk yang mendapati dirinya
telah terlempar ke dunia ini, tanpa tahu dari mana dan hendak kemana. Untuk
belajar bagaimana hidup, maka manusia pun melakukan peniruan-peniruan, sehingga
tanpa disadarinya manusia menghasrati hal-hal yang dihasrati oleh orang banyak.
Mereka menghasrati gaya hidup tertentu, obrolan tertentu, kepemilikan
artefak-artefak tertentu, komunitas pergaulan tertentu, dan lain sebagainya,
agar ia dapat hidup seperti manusia umumnya sambil mencoba mendefinisikan
identitas dirinya. Namun, dalam budaya pop, identitas itu seringkali tidak
otentik karena merupakan hasil konstruksi berbagai citraan yang ditawarkan oleh
industri massa melalui komoditi-komoditi. Dalam pandangan agama, fenomena ini
biasanya dinamakan sebagai perangkap kehidupan dunia.
Umumnya, untuk menghindari perangkap dunia ini, agama
mengingatkan para pengikutnya tentang bahaya hasrat-hasrat yang justru malah
menjebak manusia dalam perangkap kehidupan dunia sert menjauhkan mereka dari
dorongan-dorongan yang bersifat ilahiah. Secara umum hasrat tersebut bisa dikategorikan
menjadi dua hal, yaitu hasrat karnal dan libidinal. Karnal adalah
hasrat tubuh kepada sesuatu yang sifatnya material, seperti lawan jenis, harta
benda, atau makanan, dan segala hal material lainnya. Pembentukan karnal ini
sangat bergantung kepada sifat dasar (nature) dari objek karnal itu
sendiri (material) yang “bersentuhan” dengan tubuhnya. Sedangkan libidinal
adalah hasrat tubuh kepada sesuatu yang sifatnya imaterial, seperti citraan,
harga diri, status, kelas, pangkat, pujian, dan
segala hal imaterial lainnya. Dalam pembentukannya, libidinal ini lebih terarah
kepada dirinya sendiri, yaitu kepada dorongan dan kepentingannya akan pemuasan
sang ego (aspek “otak” libidinal). Imajinasi sangat berperan penting dalam
pembentukan libidinal ini, karena kepuasan libidinal sifatnya lebih imaterial,
dan dalam pertumbuhannya, libidinal sangat memerlukan kehadiran yang lain
sebagai apresiator. Dalam keseharian, seringkali kedua hasrat ini bersatu
membentuk dorongan hasrat yang termanifestasi dalam tingkah laku manusia.
Budaya pop sering dikatakan sebagai budaya remeh temeh,
banal dan bersifat melepaskan hasrat tanpa kendali. Selain itu, bentuk-bentuk
gaya hidup pop pun cenderung sekular, sehingga memunculkan reaksi dari kalangan
agama. Umumnya mereka berpendapat bahwa agama telah memberikan petunjuk dan
panduan bagaimana seharusnya manusia memilih gaya hidup yang lebih bernuansa spiritual.
Dalam beberapa agama, resistensi terhadap gaya hidup pop tersebut dinyatakan
pula secara visual, misalnya dengan atribut-atribut yang melekat dari kepala
hingga ujung kaki. Namun, sekali lagi, resistensi tersebut sangat bergantung
pada berbagai bentuk pembacaan atas teks kitab suci dan rekontekstualisasinya.
Resistensi
Gaya Hidup Gerakan Keagamaan
Berbagai resistensi
agama—baik secara visual maupun gaya hidup—terhadap kondisi budaya pop yang
banal dan miskin kedalaman spiritual, tidaklah selalu terjaga murni tujuan dan
maksud awalnya. Permasalahannya, kapitalisme dengan sentuhan tangan Raja
Midasnya mampu menyulap apa pun menjadi komoditi. Misalnya, ketika sekte
Shaker, sebuah gerakan keagamaan Kristen yang puritan, membuat seperangkat
furnitur sederhana yang mencerminkan asketisme, kapitalisme melihatnya sebagai
peluang sehingga kemudian memproduksi dan memasarkannya secara massal. Hasilnya,
furnitur tersebut pun laku keras. Fenomena itu memunculkan pertanyaan apakah masih
ada celah bagi kalangan agama melakukan resistensi? Salah satu fenomena umum
yang khas dari kalangan agama dalam melakukan resistensi adalah gerakan
keagamaan yang bersifat komunal dan masing-masing memiliki model pembacaan
kitab sucinya.
Pembacaan denotatif atas teks kitab suci
biasanya melahirkan bentuk-bentuk sikap yang harfiah dalam menampilkan agama
secara gaya hidup maupun visual. Misalnya, bahwa seorang penganut agama harus
memperlihatkan secara visual, mulai dari ujung kepala hingga kaki, segala
atribut keagamaan. Tidak jarang pembacaan denotatif ini berujung pada sikap-sikap
fundamentalistik, karena mereka cenderung menolak makna konotatif dari teks
kitab suci. Selain itu, salah satu cita-cita umum yang seringkali muncul dari
pembacaan denotatif ini adalah semangat mewujudkan negara teokrasi. Agama
diklaim sebagai satu-satunya jalan keselamatan, dan jalan keselamatan itu akan
paripurna apabila dimanifestasikan dalam bentuk tata negara. Umumnya pembacaan
denotatif ini lebih banyak muncul pada orang-orang yang baru pertama kali mulai
punya keinginan untuk belajar agama secara serius. Namun, dalam perjalanan
waktu, biasanya ada juga yang mulai bersikap kritis dan beralih ke model
pembacaan lain, tapi ada juga yang tetap bertahan dan memilih model pembacaan
denotatif ini sebagai landasan gaya hidup dan resistensinya terhadap kondisi
zaman. Selain itu, gerakan-gerakan keagamaan yang lahir dari model pembacaan
denotatif ini umumnya memiliki pandangan romantisme yang cukup kuat. Dan, dalam
tingkatan yang lebih eksplisit, pembacaan ini juga lebih sering berlandaskan
pada klaim semata. Resistensi di tingkatan ini bisa muncul bahkan hanya dari
suatu fenomena yang secara denotatif tidak sejalan.
Pembacaan konotatif atas kitab suci umumnya
dapat melahirkan sikap-sikap yang lebih moderat dari kalangan agama. Suatu
fenomena tidak serta merta dihukumi secara harfiah begitu saja melalui sebuah
teks, karena ada banyak pertimbangan, upaya rekontekstualisasi serta adaptasi
terhadap perubahan budaya dan kondisi zaman. Umumnya, pembacaan konotatif ini
lebih banyak digandrungi oleh kalangan yang memiliki landasan keilmuan dan
kesadaran kritis yang memungkinkannya untuk membaca permasalahan lebih
kontekstual dan terbuka. Pembacaan konotatif ini, setidaknya, dapat dibedakan
menjadi dua jenis, yaitu pembacaan konotatif budaya dan pembacaan konotatif mistis.
Pembacaan konotatif budaya biasanya mencoba mencari makna dari teks Kitab Suci—secara
rasional—yang merupakan kaidah dasar yang adaptif dalam menghadapi perubahan
serta kondisi zaman yang berbeda sambil tetap mempertimbangkan faktor pengaruh
budayanya. Sedangkan, pembacaan konotatif mistis adalah pembacaan yang
diperoleh dengan jalan non-rasional, dan seringkali menghasilkan tafsiran yang
terkesan melompat—ketimbang makna konotatif budaya—tapi banyak mengungkap
hal-hal yang tersembunyi dari agama. Akan tetapi, pembacaan konotatif ini
seringkali mendapat tentangan dari kalangan pembaca denotatif, bahkan bisa
sampai termanifestasi hingga tingkat kekerasan. Tampaknya, perbedaan mendasar
dari cara pembacaan denotatif dengan pembacaan konotatif adalah yang pertama umumnya
bertanya bagaimana, sementara yang kedua bertanya kenapa.
Pembacaan dekontekstual biasanya
dikemukakan oleh kalangan yang, secara serampangan, dapat dikatakan memiliki
sikap ambivalen, yaitu spiritual-enggan-sekular tak mau. Kadang cara pembacaan
ini muncul juga dari kalangan mereka yang memiliki kepentingan untuk
menunjukkan bahwa agama memiliki dimensi-dimensi keilmuan yang ilmiah seperti
dalam ilmu-ilmu modern. Namun, tak jarang pula yang terjadi justru adalah utak-atik-gatuk
paradigma ilmiah modern dengan teks Kitab Suci. Bisa jadi, motivasi dasar dibalik
pembacaan ini adalah justifikasi kepentingan atau sikap inferior dalam menghadapi
perubahan zaman. Dalam tingkatan yang lebih halus, pembacaan dekontekstual ini
juga lebih sering didasarkan pada klaim ketimbang argumen dan landasan rasional.
Pembacaan fetisistik adalah pembacaan
yang umumnya paling sering berkembang di negara-negara dunia ketiga. Secara
umum, adalah lazim bagi kalangan agama untuk menggunakan berbagai atribut
simbol keagamaan dalam kehidupan sehari-harinya, entah berupa kalung, cincin,
pakaian, dan lain sebagainya. Namun, yang menjadi unik adalah ketika
atribut-atribut tersebut dipercaya dapat mendatangkan kekuatan, keberuntungan
atau kesucian bagi yang memakainya. Ada yang menjadikan tulisan-tulisan ayat
suci sebagai jimat untuk kekuatan tertentu. Ada juga yang menjadikan tulang
figur suci atau barang kepunyaannya sebagai sesuatu yang akan mendatangkan
kekuatan dan keuntungan tertentu. Kepercayaan seperti ini sering diidentikkan
dengan tingkat intelektualitas dan kelas sosial yang rendah dari suatu kelompok
masyarakat. Akan tetapi, sebenarnya banyak juga kalangan yang memiliki
intelektualitas dan kelas sosial lebih tinggi yang juga memiliki kepercayaan
seperti ini. Pembacaan ini mengesankan bahwa dengan menggunakan sesuatu yang
material, manusia dapat mengatasi kehidupan secara imaterial melalui kekuatan
dari objek-objek fetis tersebut. Di samping itu, pembacaan ini memiliki potensi
resis terhadap berbagai hal rasional yang mementahkan tafsir yang dihasilkan.
Pembacaan dekonstruktif adalah pembacaan
yang paling lazim muncul dalam komunitas budaya pop. Pembacaan ini lebih banyak
didasarkan pada segala hal yang bersifat populer, seperti imajinasi, cara
berpikir dan argumen yang dangkal (common
sense). Salah satu kekuatan budaya pop adalah mengarahkan perhatian manusia
hanya kepada aspek-aspek permukaan dari segala hal, kepada hal-hal yang remeh
lagi banal. Cara pembacaan dekonstruktif ini tidaklah sama dengan dekonstruksi,
karena cara pembacaan ini umumnya justru lahir dari keawaman, ketaksadaran,
serta hasrat komunal. Aspek citraan dan kemasan merupakan faktor utama yang
digunakan dalam pembacaan ini. Ketimbang melakukan resistensi terhadap
aspek-aspek budaya pop yang memiliki banyak sifat duniawi, para pelaku
pembacaan dekonstruktif malah menceburkan dirinya dalam kancah budaya pop
sembari meyakini bahwa agama pun mengajarkan hal seperti itu. Atau, dengan kata
lain, sifat dasar agama yang cenderung resis terhadap yang budaya justru malah
dinetralisir oleh pembacaan ini dengan melabeli yang budaya (pop) itu sendiri
sebagai agama.
[1] Yasraf Amir Piliang, ‘Tafsir Atas Tafsir Al-Qur’an:
Sebuah Pendekatan Cultural Studies’, makalah yang disampaikan dalam acara
Seminar & Mukernas Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Se-Indonesia
(FKMTHI), dengan tema “Living Quran: Al-Quran Dalam Fenomena Sosial dan
Budaya”, diselenggarakan oleh FKMTHI, BEMJ Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 13-17 Maret 2005.
[3] Lihat Ernest Gellner, Menolak Posmodernisme: Antara
Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius, terbitan Mizan (1994).
N.B. Naskah ini diterbitkan atas izin penulis sendiri (Pak Alfathri Adlin) setelah kami meminta beliau untuk ikut menyumbangkan ide-ide lewat tulisan beliau di blog LPPMD ini.