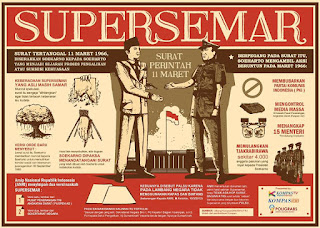Sejak
kemunculannya di tahun 1966, Supersemar masih menjadi perbincangan yang memicu
perdebatan panjang hingga
hari ini. Sebagian masyarakat menilai Supersemar sebagai salah satu tonggak
peristiwa bersejarah di Indonesia. Mungkin saja tafsiran semacam ini muncul
ketika melihat pengaruh Supersemar bagi tatanan sosial dan politik di Indonesia—masyarakat menilai
Supersemar membuka jalan bagi era pemerintahan yang baru.
Saat itu kondisi
ekonomi politik di Indonesia dalam keadaan tidak stabil, Demokrasi Terpimpin
yang digaungkan oleh Sukarno menyeret Indonesia ke berbagai macam permasalahan.
Rakyat seperti begitu tak sabarnya menanti perbaikan sistem pemerintahan yang
berorientasi kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, berbagai gejala politik-sosial
yang mewarnai era Demokrasi Terpimpin membuat perhatian terhadap sektor ekonomi
kian terkikis. Berbicara Supersemar dan masa transisi pemerintahan adalah berbicara mengenai pertarungan ideologi
politik di Indonesia.
Informasi
terkait Supersemar yang muncul dalam berbagai versi menimbulkan distorsi
sejarah tersendiri. Bahkan ketika Supersemar akan melewati peringatannya yang
ke-50, distorsi Sejarah ini belum mampu juga menemukan penyelesaiannya. Kalau
boleh dibilang, Supersemar sifatnya sangat politis di dalam sejarah dinamika
Republik Indonesia. Unsur politis ini memiliki hubung-kait dengan distorsi
sejarah yang ada, ketika penulisan sejarah diarahkan kepada kepentingan
pemimpin kala itu. Celakanya, Sejarah yang dikisahkan kemudian menjadi cerita
yang diterima di tengah masyarakat.
Pun pada kenyataannya berbeda dengan peristiwa
sejarah itu sendiri. Inilah yang terjadi dengan Supersemar dan pengkisahan di
balik peristiwanya. Betapa hegemoni Orde Baru mampu menyajikan kisah sejarah
yang bersifat tendensius terhadap suatu paham dan menafikan paham lain di satu
sisi. Kita sedang berbicara pertarungan ideologi kiri dan ideologi Pancasila.
Supersemar,
dalam beberapa versi, diyakini sebagai surat mandat yang diberikan oleh
Presiden Sukarno kepada Suharto untuk memulihkan ketertiban dan keamanan Negara
pascagejolak 30 September 1965. Dan perintah ini ditafsirkan oleh Suharto
sebagai perintah pembubaran PKI dan organisasi yang berlandaskan ideologi
komunis lainnya. Suharto rupanya menafsirkan seperti itu karena menilai
keamanan akan tercapai hanya jika PKI dibubarkan. Suharto pun hanya terfokus
pada poin pemulihan keamanan ini saja—poin
kedua di dalam Supersemar,
yang berisi perintah untuk melindungi keluarga Presiden beserta seluruh harta
dan karyanya, tidak dipenuhi oleh Suharto. Selepas menafsir mandat Supersemar,
ia kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 yang
ditandatanganinya pukul 04.00 Sabtu, 12 Maret 1966. Ini adalah sebuah tindakan
yang sangat berani, sekaligus tidak menghormati posisi Sukarno sebagai presiden
kala itu.
Suharto pun
menginisiasi aksi massa terkait Supersemar yang menjaring simpati dari rakyat,
mahasiswa, dan para pemuda. Aksi yang digelar ini semakin memupuk keberanian
Suharto untuk melakukan penyelesaian terhadap eksekusi golongan kiri di
Indonesia. Selesai pembubaran, Presiden Sukarno yang dinilai dekat dengan (golongan) kiri pun disalip
posisinya sehingga melalui rangkaian Sidang Umum MPRS tahun 1966, Suharto
berhasil naik dan menggeser kekuasaan Sukarno. Dinamika politik yang terjadi
kala itu menjadi catatan besar dalam sejarah perpolitikan Indonesia, mengingat
Suharto merupakan orang biasa, namun pada akhirnya mampu menjatuhkan Sukarno
yang telah memiliki nilai integritas di tengah kehidupan rakyatnya.
Hegemoni Suharto
di masa Orde Baru membuat banyak penulisan sejarah tak sesuai dengan peristiwa
yang sebenarnya, terutama peristiwa sejarah menjelang lengsernya Sukarno.
Banyak terjadi perombakan alur pengkisahan yang disandarkan pada kepentingan
Orde Baru dalam menjaga stabilitas dan pertahanan Negara, kalau tidak bisa
dibilang sebagai upaya pembungkaman terhadap kebenaran.
Rakyat Indonesia
menikmati cerita-cerita rekaan terutama dalam kisah pemberontakan 30 September,
peristiwa yang menghantarkan Supersemar. Ketika rezim Suharto akhirnya
tumbang—meski masih tersisa kelompok Orde Baru di masa Reformasi ini—sejarah
yang dulu diyakini sebagai kebenaran mutlak perlahan mulai diragukan karena
munculnya tulisan-tulisan yang mengungkapkan kisah dari perspektif yang
berbeda. Golongan kiri mulai dapat bernapas lega ketika akhirnya Suharto
lengser, karena pembungkaman akhirnya berakhir. Banyak aktivitas upaya
pelurusan sejarah yang digalakan oleh aktivis kiri. Berakhirnya rezim Suharto
seperti memberikan semangat bagi golongan kiri untuk melanjutkan pembangunan
ideologi kiri di Indonesia. Dan, sebagian orang beranggapan, aktivis kiri dapat
membantu pelurusan sejarah yang selama ini dibelokkan oleh kepentingan Orde
Baru.
Permasalahan
dalam hal ini saya pikir adalah mengenai historiografi atau penulisan sejarah.
Memang betul, adagium yang menyatakan “Sejarah adalah milik pemenang”, hal ini
terbukti dari kendali Suharto atas setiap penulisan sejarah yang diterbitkan.
Akan tetapi, hari ini banyak upaya untuk meluruskan sejarah yang digalakkan berbagai pihak,
terutama golongan kiri, yang memiliki banyak singgungan dengan pembelokan
sejarah yang dilakukan semasa Orde Baru. Ini dapat menjadi momentum kebangkitan
gerakan kiri—mengingat
pertarungan politik di Indonesia adalah tentang pertentangan golongan kiri
melawan golongan di luarnya.
Ucu Feni (Sekretaris Umum LPPMD Unpad 2015-2016, mahasiswi Ilmu Sejarah 2014)